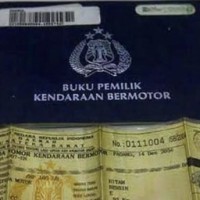JATIMTIMES - Di pinggir pantai utara Jawa Timur, sekitar dua belas kilometer dari pusat kota Gresik, berdirilah sebuah petilasan sunyi yang justru menorehkan bukti arkeologi Islam tertua di Nusantara. Leran, dusun di Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, telah lama menjadi persinggahan para peziarah yang ingin memetik hikmah dari sebuah batu nisan. Batu nisan itu bukan sekadar simbol makam, melainkan prasasti penanda hadirnya sebuah keyakinan dan jejak migrasi yang menembus zaman: Makam Fatimah binti Maimun bin Hibatallah.
Nama Fatimah binti Maimun jarang muncul dalam buku sejarah resmi, tetapi batu nisannya justru mencatat kronogram tahun 475 Hijriah, atau 1082 Masehi. Di situlah bermula sebuah petualangan panjang menelusuri bagaimana Islam datang dan berakar di tanah Jawa, jauh sebelum para wali sembilan menjadi legenda di pesisir utara. Dari batu nisan itulah, seberkas cahaya membuka tabir migrasi kaum Lor asal Persia, persinggungan budaya Hindu-Buddha, hingga pergulatan makna spiritualitas yang menumbuhkan jaringan dagang internasional di sepanjang pesisir utara Jawa.
Kronologi Batu Nisan Tertua: Membaca Sebuah Prasasti
Baca Juga : 400 Model Cilik Tampil Memukau Bawakan Karya Desainer Pendatang Baru di Malang Fashion Runway 2025
Pengetahuan tentang keberadaan makam ini pertama kali diulas secara serius oleh J.P. Moquette pada awal abad ke-20. Dalam tulisannya De Oudste Mochammadaansche Inscriptie op Java (op de Grafsteen te Leran), Moquette membaca inskripsi Arab pada batu nisan Fatimah dengan hati-hati. Baris demi baris menyingkap pengakuan mendalam tentang kefanaan hidup:
Bismillâhirrahmânirrahim. Kullu man alaihâ fânin wa yabqâ wajhu rabbika dzul jalâli wal ikrâm.
Hâdzâ qabru syâhidah Fâthimah binti Maimûn bin Hibatallâh, tuwuffiyat fi yaumi al-Jum‘ah min Rajab wa fi sanati khamsatin wa tis‘ina wa arba‘ati miatin ilâ rahmat Allâh. Shadaqallâh al-‘azhim wa rasûlihi al-karîm.
Terjemahan atas prasasti ini oleh Prof. H.M. Yamin mempertegas makna spiritualnya: bahwa setiap makhluk hidup adalah fana, sedangkan wajah Tuhan yang penuh keagungan tetap kekal. Maka batu nisan ini tidak hanya berbicara tentang kematian, tetapi juga tentang keabadian keyakinan yang dibawa sang syahidah, Fatimah binti Maimun.
Menariknya, Moquette membaca kronogram pada inskripsi ini sebagai 475 Hijriah (1082 M). Sementara sebagian pakar lain, berdasarkan variasi bacaan, menafsirkan 495 H (1101 M). Penanggalan inilah yang kemudian dipertajam oleh Jere L. Bacharach melalui konversi kalender hijriah-masehi, meneguhkan bahwa prasasti Leran memang berasal dari rentang akhir abad ke-11. Bagi sejarawan arkeologi Islam, perbedaan beberapa dekade hanyalah pernik. Yang terpenting: prasasti ini menyalakan lentera bahwa Islam telah menjejak di Jawa jauh sebelum riwayat Syekh Maulana Malik Ibrahim dan para wali songo.
Leran Sebagai Titik Singgung Jalur Perdagangan dan Dakwah
Bagaimana mungkin sebuah makam tua bertuliskan kufi Arab berdiri di pesisir Jawa pada abad ke-11? Jawabannya terletak pada posisi strategis Leran. Dalam Laporan Penelitian Arkeologi di Situs Pesucian (1994–1996), Leran dicatat pernah berfungsi sebagai pemukiman perkotaan dan pusat perdagangan. Bukti arkeologis berupa temuan mangkuk-mangkuk keramik dari abad ke-10 dan ke-11 mengindikasikan adanya jejaring niaga lintas benua: ke utara terhubung dengan Cina, ke selatan bersinggungan dengan India, dan ke barat membentang ke Persia serta Timur Tengah.
Jaringan ini tidak semata memperdagangkan barang, tetapi juga gagasan dan keyakinan. Sebagaimana dikemukakan Hasan Muarif Ambary dalam Menemukan Peradaban, ayat Al-Qur’an dari Surah Ar-Rahman yang tergores di batu nisan Fatimah berkorespondensi dengan tradisi Islam awal yang berkembang di wilayah Champa. Bahkan, jenis huruf kufi pada prasasti Leran memiliki kemiripan dengan makam kuno di Pandurangga (Panh-Rang), Vietnam bagian selatan. Kedekatan epigrafis ini menegaskan adanya arus migrasi ulama, pedagang, dan pelaut Muslim di sepanjang pesisir Asia Tenggara.
Suku Lor dan Jejak Persia: Mengurai Identitas Sang Syahidah
Sejarawan sepakat, gelombang migrasi awal Islam ke Jawa salah satunya dibawa oleh kaum Lor, yakni suku pendatang asal Persia yang menetap di berbagai pesisir Nusantara sejak abad ke-10. Nama “Loram” atau “Leran” sendiri diperkirakan berasal dari komunitas Lor ini. Dalam konteks Fatimah binti Maimun, batu nisan yang memuat nama bin Hibatallah mencerminkan pola penamaan Arab-Persia, sekaligus menyingkap identitas kulturalnya.
Menarik untuk dicatat, kata asy-Syahidah yang terukir di prasasti dapat dibaca ganda. H.M. Yamin menafsirkan sebagai ‘korban syahid’, sejalan dengan narasi seorang wanita beriman yang wafat menjaga keyakinannya. Akan tetapi, pembacaan lain menafsirkan asy-Syahidah sebagai ‘pemimpin wanita’. Tafsir kedua ini membuka ruang kemungkinan bahwa Fatimah bukan sekadar figur pasif, tetapi berperan sebagai pemimpin komunitas kecil di Leran. Ia barangkali menjadi tokoh spiritual sekaligus penopang jaringan dagang di antara para pemukim Persia.
Leran, Toponim Suci di Pesisir Majapahit
Arkeologi tidak berdiri sendiri. Bukti prasasti Leran abad ke-13 yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta menambah lapis interpretasi tentang status kawasan ini. Dalam prasasti tembaga berbahasa Jawa Kuno, Leran disebut sebagai tanah perdikan (sima) yang bebas pajak, dengan batas-batas wilayah yang sakral: padang rumput milik Si Dukut, tambak milik Si Bantawan, dan susuk ri batwan sebagai tempat suci.
Muncul pertanyaan: apakah susuk ri batwan itu merujuk pada situs makam Fatimah binti Maimun? Dugaan kuat mengarah ke sana. Di tengah dominasi Hindu-Buddha pada masa Singasari-Majapahit, identitas keislaman makam ini kemungkinan memudar, menjelma menjadi susuk, tempat keramat yang dihormati masyarakat lokal. Menurut pembacaan naskah Kunjarakarna, istilah kuti dalam Sanskerta dapat bermakna biara Buddha atau gubuk pertapaan. Simbol kutik dalam prasasti Leran bisa mencerminkan bagaimana sebuah makam Islam lambat laun diresapi makna baru, diterima sebagai petilasan suci lintas keyakinan.
Makam Tua di Tengah Komunitas Syi’ah Persia
Baca Juga : Jangan Salah Paham! Ini Arti Rambu Hijau, Biru, dan Cokelat di Jalan Tol
Kajian epigrafis pada batu nisan di sekitar makam Fatimah binti Maimun menunjukkan pola ragam hias abad ke-16, dengan inskripsi kufi berisi doa-doa kepada Allah. S.Q. Fatimi dalam Islam Comes to Malaysia berpendapat, gaya tulisan kufi tersebut mendekati tradisi Syi’ah. Hipotesis ini menguatkan dugaan bahwa komunitas Lor di pesisir Leran merupakan keturunan migran Persia penganut Syi’ah, yang pada masa awal membaur dengan masyarakat setempat.
Gema spiritualitas Syi’ah di Leran juga terekam pada tradisi lisan tentang kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Konon, ulama besar perintis dakwah Islam di Jawa itu, yang dikenal sebagai Sunan Gresik, pertama kali menjejakkan kaki di Desa Sembalo di sebelah Leran pada akhir abad ke-14. Di sana, ia mendirikan masjid dan membentuk komunitas Muslim. Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mencatat bagaimana Maulana Malik Ibrahim tinggal bersama para Mahomedans lain di Leran, membina komunitas Islam yang kemudian menancapkan pengaruh hingga Gresik dan sekitarnya.
Jaringan Kekuasaan, Spiritualitas, dan Dakwah
Dari sudut pandang historiografi kritis, keberadaan makam Fatimah binti Maimun menandakan sebuah pola: migrasi membawa ideologi, membentuk komunitas, lalu membangun jaringan kekuasaan simbolik. Para pemukim Lor tidak hanya berdagang, tetapi juga memelihara simbol-simbol suci untuk mempertahankan ikatan kultural. Sebuah makam tua berprasasti kufi di pesisir utara Jawa adalah bukti paling kasatmata bagaimana spiritualitas dapat bertahan, sekalipun di tengah arus dominasi Hindu-Buddha yang lebih mapan.
Dalam konteks inilah dapat dipahami mengapa masyarakat setempat memuliakan Fatimah binti Maimun sebagai sosok asy-Syahidah. Di tengah ketegangan agama dan politik pesisir abad ke-11 hingga ke-13, figur perempuan pun dapat menjadi pusat ziarah, memancarkan aura kramat yang dirawat lintas generasi. Seiring berjalannya waktu, para pendakwah seperti Maulana Malik Ibrahim memanfaatkan legitimasi spiritual makam ini untuk membentuk basis dakwah baru di Leran dan Gresik.
Makna dan Warisan: Ketika Batu Nisan Berbicara
Apakah yang menjadikan batu nisan Fatimah binti Maimun begitu bermakna? Pertama, ia memancarkan kontinuitas keyakinan. Huruf kufi pada prasasti menjadi jejak tertua kedatangan Islam di Nusantara yang dapat diverifikasi secara arkeologis. Kedua, ia membuktikan dinamika akulturasi: toponim Leran memuat tapal batas (Wangen), tempat suci (Pasucian), tempat kaum ningrat (Penganden), vihara Buddha (Kuti), hingga penanda kemerahan (Daha). Keseluruhan lanskap toponim ini menegaskan bahwa situs makam berada di wilayah sakral, bebas pajak, dan dihormati lintas keyakinan.
Ketiga, ia menuturkan kisah migrasi Persia ke Jawa melalui jalur niaga Samudra Hindia. Jaringan ini bukan sekadar membawa barang dagangan, tetapi juga gagasan kosmopolitanisme Islam yang kelak mewarnai wajah kerajaan-kerajaan pesisir di Jawa Timur.
Hari ini, peziarah yang berangkat dari Surabaya atau Gresik dapat menempuh Leran melalui jalur tol Manyar. Sebuah papan petunjuk di pinggir jalan raya menuntun ke cungkup sederhana yang melindungi batu nisan sang syahidah. Di sekitar makam Fatimah binti Maimun, makam-makam tua lainnya berserak — membisikkan kisah tentang para pendahulu yang mewariskan keyakinan, budaya, dan semangat dagang lintas benua.
Di tanah yang pernah menjadi perdikan sima ri Leran, kisah spiritualitas Islam, migrasi Persia, hingga jejaring niaga Samudra Hindia berpadu menjadi mosaik sejarah. Makam Fatimah binti Maimun bukan sekadar prasasti, melainkan penanda awal bagaimana Islam menjejak di tanah Jawa — sunyi, terlupakan, tetapi abadi di dalam batu.