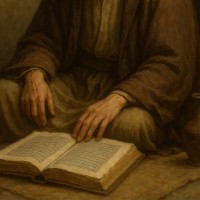JATIMTIMES - Pada permulaan abad ke-20, Surakarta bukan hanya menjadi pusat kebudayaan Jawa yang kaya akan tradisi, melainkan juga tampil sebagai laboratorium awal modernisasi di jantung Jawa. Salah satu sosok kunci yang menandai transformasi besar tersebut adalah Susuhunan Pakubuwono X, seorang raja yang dengan visi progresifnya memadukan adat tradisional dengan semangat kemajuan teknologi.
Masa pemerintahannya dari tahun 1893 hingga 1939 menjadi tonggak penting bagi perkembangan infrastruktur kota, terutama dalam bidang air bersih, listrik, dan komunikasi radio.
Baca Juga : Waspada! Fenomena Bediding Bisa Picu Penyakit Ini
Membangun Sarana Air Bersih: Dari Cakratulung ke Gorong-Gorong Kota
Tahun 1926 menandai tonggak monumental dalam sejarah penyediaan air bersih di Surakarta. Sebuah perusahaan bernama NV Hoogdruk Waterleideng (Perusahaan Air Minum Tekanan Tinggi) didirikan dengan sumber air di Cakratulung, Delanggu, Klaten. Perusahaan ini dibiayai secara kolektif oleh pemerintah Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran, sebagai simbol sinergi dua entitas politik utama Surakarta dalam mewujudkan pelayanan publik modern.
Saluran air tersebut dialirkan langsung ke rumah-rumah penduduk kota, sebuah kemewahan yang sebelumnya tak terbayangkan. Enam tahun kemudian, sistem ini diperluas dengan pembangunan gorong-gorong yang menjadi sarana pembuangan air hujan, menandai awal mula sistem drainase perkotaan yang terencana.
Kesadaran akan pentingnya air tidak hanya sebatas utilitas perkotaan. Pakubuwono X juga memperhatikan sumber-sumber air alam yang diyakini memiliki khasiat pengobatan. Di Sragen, Sendang Ngunut dipelihara dengan baik, demikian pula Pasanggrahan Langenharja di Sukoharjo yang terkenal dengan air hangat alaminya. Kedua tempat ini dijaga oleh abdi dalem jurukunci dan terbuka untuk umum tanpa pungutan biaya, mencerminkan kebijakan sosial Pakubuwono X yang berpihak pada kesehatan rakyat.
Penerangan Kota: Dari Lampu Ting ke Solosche Electriciteits-Maatschappij
Sebelum listrik diperkenalkan, malam di Surakarta dihiasi kegelapan. Penerangan bergantung pada lampu ting, yakni lampu minyak yang diletakkan setiap 100 meter di jalan-jalan utama. Terbuat dari kaleng dengan sumbu dan kaca pelindung, lampu ini mudah mati bila hujan deras atau tertiup angin. Ini mencerminkan keterbatasan teknologi yang dihadapi kota pada awal abad ke-20.
Namun pada 19 April 1902 (malam Sabtu tanggal 10 Sura tahun Be 1832), sebuah peristiwa penting terjadi. Lampu listrik untuk pertama kalinya menyala di kota Solo, menandai era baru penerangan kota. Peristiwa tersebut didukung penuh oleh Kasunanan, Mangkunegaran, serta para saudagar dan hartawan yang mendirikan Solosche Electriciteits-Maatschappij (SEM). SEM inilah yang menjadi pelopor pembangkit listrik tenaga diesel di kota itu.
Pembangunan jaringan listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga simbol peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat yang siap menyambut modernitas. Pakubuwono X sadar bahwa cahaya listrik tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga menandai hadirnya peradaban baru.
Komunikasi Massa: Dari NIROM hingga SRV
Tahun 1930 menjadi tonggak penting lain ketika stasiun radio pertama di Hindia Belanda mulai mengudara. Dikenal sebagai NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij), siarannya terbatas pada musik dan lagu berbahasa Belanda, mencerminkan dominasi budaya kolonial.
Namun Surakarta kembali tampil sebagai pionir dalam menghadirkan suara pribumi ke ruang publik. Pada tanggal 1 April 1933, didirikan Solosche Radio Vereniging (SRV), sebuah perkumpulan radio lokal yang mengudara dari Jalan Ronggowarsito. Berbeda dengan NIROM, SRV aktif menyiarkan lagu-lagu karawitan Jawa, memperdengarkan identitas budaya lokal kepada publik. Pada 5 Januari 1934, SRV mulai siaran secara rutin dengan transmitter baru.
Pada Februari 1936, Pemerintah Kasunanan bahkan membangun stasiun radio sendiri bernama SRI (Siaran Radio Indonesia). Studio SRI berada di kediaman Gusti Pangeran Harya Suryoamijoyo. Dengan siaran dalam bahasa Jawa, radio ini menjadi kanal komunikasi massa yang menjangkau berbagai kalangan, dan memperkuat eksistensi budaya lokal di tengah dominasi kolonial.
Transformasi Surakarta tak hanya berlangsung di langit dan udara, tetapi juga di darat. Dalam masa pemerintahan Pakubuwono X, didirikan bangunan-bangunan yang disebut "Rumah Pos"—tempat perhentian kereta kuda dan tempat istirahat para pembesar yang bepergian jauh. Rumah Pos ini tersebar di titik strategis seperti Banyuanyar, Jurug, Karanganyar, Bangsri, Nambangan, dan Baturetna. Fungsinya serupa dengan sistem rest area modern, dan menegaskan pentingnya infrastruktur darat dalam menghubungkan pusat kota dengan wilayah-wilayah pinggiran.
Modernisasi dan Kesadaran Politik
Modernisasi di bawah Pakubuwono X tidak berlangsung dalam ruang hampa. Periode ini juga menyaksikan geliat kebangkitan nasional dan tumbuhnya kesadaran politik di kalangan kaum priyayi dan intelektual Jawa. Kemajuan teknologi seperti listrik dan radio secara tidak langsung memperkuat semangat kolektif dan memperluas jangkauan informasi.
Pakubuwono X dikenal sebagai raja yang berwawasan luas dan toleran terhadap gagasan pembaruan. Ia memelihara hubungan baik dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional serta mendukung kegiatan budaya dan pendidikan. Perpaduan antara budaya tradisional dan modernitas inilah yang membuat masa pemerintahannya dikenang sebagai masa keemasan Surakarta.
Jejak modernisasi yang diwariskan Pakubuwono X masih dapat dirasakan hingga hari ini. Sistem distribusi air bersih yang dibangun pada 1926 menjadi cikal bakal PDAM modern. Listrik yang pertama kali menyala di Solo pada 1902 kini telah berkembang menjadi jaringan PLN yang menjangkau pelosok. Radio lokal seperti SRV membuka jalan bagi siaran budaya yang hari ini dilanjutkan dalam bentuk radio komunitas dan siaran televisi lokal.
Lebih dari sekadar peninggalan fisik, modernisasi ala Pakubuwono X mencerminkan cara pandang yang progresif dan visioner dari seorang raja Jawa terhadap perubahan zaman. Ia tidak menolak Barat, tetapi mengadopsi aspek-aspek yang berguna, sembari tetap menjaga marwah dan jati diri budaya Jawa. Inilah yang membedakan modernisasi Pakubuwono X dari model pembangunan kolonial: berakar pada rakyat, bersandar pada tradisi, dan terbuka pada masa depan.
Sejarah Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono X bukan sekadar cerita tentang teknologi. Ia adalah narasi tentang manusia, kekuasaan, dan kehendak untuk berubah. Sebuah cermin tentang bagaimana budaya dan modernitas bisa bersatu dalam bingkai yang harmonis, jika dipandu oleh pemimpin yang bijaksana dan visioner.
Dalam konteks historiografi, warisan Pakubuwono X adalah penanda bahwa modernisasi bukan monopoli negara kolonial, tetapi juga merupakan proyek elite pribumi yang sadar akan urgensi perubahan. Dokumentasi sejarah dari koran-koran sezaman seperti Harian Candrakanta (Mei 1902), Harian Darmo Kondho (Januari 1926), dan catatan pemerintah lokal menjadi saksi bisu atas langkah-langkah besar yang ia tempuh.
Pakubuwono X bukan hanya penguasa tradisional. Ia adalah seorang arsitek masa depan.
Pakubuwono X: Cahaya Keemasan dari Surakarta Hadiningrat
Di antara deretan panjang penguasa Kasunanan Surakarta Hadiningrat, nama Pakubuwono X terukir dengan tinta emas sebagai raja yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga visioner. Di tengah masa penjajahan, saat tanah Jawa bergolak oleh perubahan politik dan sosial, seorang raja Jawa justru tampil dengan sosok tegas, berpengetahuan luas, dan gemar membangun. Dialah Sri Susuhunan Pakubuwono X, sang raja tambun yang menyalakan terang di Surakarta.
Pakubuwono X lahir pada 29 November 1866 di lingkungan keraton Surakarta. Nama kecilnya adalah Raden Mas Sayidin Malikul Kusno. Ia merupakan putra dari Susuhunan Pakubuwono IX dengan permaisuri Kanjeng Ratu Ayu Kustiyah. Sejak usia belia, tepatnya saat ia baru berumur tiga tahun, Raden Kusno telah ditetapkan sebagai putra mahkota. Gelar yang disematkan kepadanya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram—gelar panjang yang menunjukkan betapa besar harapan Keraton Surakarta pada dirinya.
Baca Juga : Pojok Baca Soekarno Hadir di Unisba Blitar, Rawat Ingatan Kolektif Mahasiswa
Didikan ketat, penuh nilai adiluhung, membentuk karakter Raden Kusno menjadi pribadi yang tekun dan cerdas. Seiring pertumbuhannya, ia dikenal menguasai banyak bidang keilmuan. Tidak hanya ilmu pemerintahan dan politik, Raden Kusno juga mendalami sejarah, filsafat, hingga ilmu keris dan olah kanuragan. Kemampuannya dalam memainkan rebab dan memahami pakem wayang menjadikannya raja yang sangat dekat dengan denyut kebudayaan Jawa.
Pakubuwono IX wafat pada 16 Maret 1893. Dua minggu kemudian, tepat pada 30 Maret 1893, Raden Kusno dinobatkan menjadi raja Surakarta dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa. Ia memerintah selama 46 tahun, menjadikannya penguasa Kasunanan Surakarta terlama sepanjang sejarah.
Sejak awal pemerintahannya, Pakubuwono X menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat. Ia tidak sekadar mempertahankan simbolisme keraton, tetapi juga menyadari pentingnya modernisasi. Dalam pandangannya, kemegahan kerajaan harus ditopang dengan kemajuan budaya dan teknologi.
Masa pemerintahan Pakubuwono X dikenal sebagai era keemasan kebudayaan Jawa. Di tangannya, kesenian keraton hidup dengan napas baru. Gamelan, tari-tarian, seni pedalangan, karawitan, hingga batik tumbuh subur. Banyak gendhing diciptakan dan pakem tari dibakukan. Sentana dalem dan para abdi dalem pun didorong aktif dalam kegiatan seni, menjadikan lingkungan keraton sebagai pusat kebudayaan yang semarak.
Kecintaan Pakubuwono X terhadap budaya tidak bersifat elitis. Ia membuka akses bagi rakyat umum melalui pergelaran seni di Taman Sriwedari. Wayang orang dan pentas musik digelar secara rutin, membentuk identitas kota Surakarta sebagai kota budaya. Bahkan hingga kini, warisan ini masih bisa dirasakan denyutnya.
Abdi dalem keraton menyebut Pakubuwono X dengan gelar istimewa: "Sampeyan Dalem Ingkang Minulyo saha Wicaksana"—gelar yang mencerminkan kedalaman ilmunya serta keluhuran budinya.
Di balik jubah kebesaran dan kesetiaan pada tradisi, Pakubuwono X adalah raja yang sangat modern. Ia memadukan nilai lokal dengan arsitektur dan teknologi dari Barat. Beberapa bangunan peninggalannya, seperti atap Argapura yang bergaya loji Belanda dan patung-patung Eropa di lingkungan Sasana Sewaka serta Sasana Hadrawina, adalah bukti nyata dari sinergi estetika Timur dan Barat.
Pakubuwono X tidak hanya membangun gedung, tetapi juga memperkuat infrastruktur kota. Ia menjadi pionir dalam pembangunan sarana penerangan listrik di Hindia Belanda. Pada tahun 1902, Kota Surakarta menjadi kota pertama yang menikmati cahaya listrik secara massal, bahkan sebelum Batavia.
Perusahaan listrik itu dibentuk oleh sinergi antara keraton Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, saudagar Tionghoa, dan para bangsawan lokal. Mereka mendirikan Solosche Electriciteit Maatschappij (SEM), sebuah perusahaan listrik modern. Tanggal 19 April 1902 menjadi momen bersejarah ketika Surakarta dinyalakan oleh cahaya lampu listrik untuk pertama kalinya.
Dengan listrik sebagai penopang utama, geliat malam Surakarta menjadi hidup. Taman hiburan, pertunjukan wayang, dan kegiatan sosial lainnya berkembang pesat. Kehadiran penerangan ini juga mendorong kegiatan literasi dan distribusi pengetahuan.
Pakubuwono X bahkan menjadi pelanggan berbagai surat kabar berbahasa Belanda, Melayu, dan Jawa. Beberapa surat kabar yang populer kala itu antara lain Neratja, Bromartani, Dharma Khanda, Sin Po, Soerabajaasch Handelsblad, De Java Bode, dan Sedia Utama. Keraton Surakarta menjelma menjadi pusat pemikiran dan pergaulan intelektual di tanah Jawa.
Pakubuwono X tidak hanya dikenal sebagai raja yang cerdas dan estetis, tetapi juga sebagai pemimpin yang dermawan. Hartanya yang melimpah sering digunakan untuk membantu rakyat, membangun fasilitas umum, serta mendanai kegiatan seni dan pendidikan. Ia juga dekat dengan para saudagar, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal dari berbagai kalangan.
Pada masa sulit menjelang kemerdekaan, ia memainkan peran sebagai penyeimbang antara tradisi dan modernitas, antara kepentingan rakyat dan pemerintah kolonial. Walau berada dalam bayang-bayang kekuasaan Belanda, Pakubuwono X menunjukkan sikap diplomatis yang penuh perhitungan. Ia tetap menjaga marwah keraton tanpa harus mengorbankan stabilitas kerajaannya.
Pakubuwono X wafat pada 22 Februari 1939. Duka menyelimuti seluruh Surakarta dan tanah Jawa. Ia dimakamkan di Astana Imogiri, Yogyakarta, tempat peristirahatan para raja Mataram.
Meski telah tiada, warisan Pakubuwono X tetap hidup dalam bentuk bangunan, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang ia tanamkan. Gedung-gedung berarsitektur campuran Jawa-Eropa, gamelan yang masih ditabuh dalam tradisi keraton, hingga semangat sinergi lintas golongan seperti dalam pembangunan listrik, menjadi jejak keemasan sang raja.
Pakubuwono X bukan hanya simbol kejayaan Surakarta, tetapi juga lambang kejayaan peradaban Jawa dalam menghadapi arus modernitas. Dalam dirinya melebur nilai tradisi, kecintaan pada budaya, dan keberanian melangkah ke masa depan.