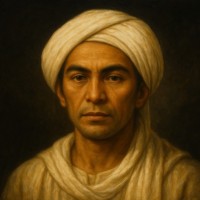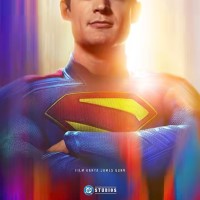JATIMTIMES - Dalam khazanah sejarah Islam Nusantara, nama Raden Umar Said atau lebih masyhur dikenal dengan sebutan Sunan Muria, kerap muncul di antara kepingan babad, tradisi tutur, serta hikayat yang berserakan di lereng pegunungan Muria, Jepara, Kudus, hingga pesisir utara Jawa Tengah.
Seperti halnya tokoh-tokoh Wali Songo lainnya, jejak spiritual dan intelektual Sunan Muria kerap berdiri di persimpangan antara kenyataan historis, mitos lokal, dan simbolisme sufistik yang terus hidup di masyarakat.
Baca Juga : Gandeng Perusahaan Tiongkok, Unikama Buka Akses Magang Internasional bagi Mahasiswa PTS
Melacak rantai keilmuan Sunan Muria berarti pula menelusuri aliran pengetahuan yang menautkan jalur asketisme lokal, transformasi spiritualitas Majapahit akhir, hingga strategi dakwah Islam Jawa yang fleksibel dalam membingkai laku ritual ke dalam bahasa budaya setempat.
Asal-usul dan Konteks Sosial
Nama Sunan Muria secara genealogi lekat dengan Sunan Kalijaga, salah satu tokoh Wali Songo yang paling luas pengaruhnya di tanah Jawa. Raden Umar Said dikenal sebagai putra Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, putri Maulana Ishaq. Jalur inilah yang menempatkan Sunan Muria satu generasi di bawah Sunan Kalijaga, dengan gelar Raden Umar Said sebagai nama mudanya.
Versi ini kerap didukung dengan narasi perjalanan Sunan Kalijaga yang konon pernah berguru ke Pasai, menemui Syaikh Dara Putih, adik Syaikh Jumadil Kubra, dan kemudian menikahi Dewi Sarah. Dari sinilah, hubungan spiritual antara penyebar Islam Jawa dan jaringan ulama Pasai terlihat nyata. Jejak ideologi sufistik—penyebaran Islam melalui seni tembang, wayang, dan suluk—juga senada dengan metode dakwah Kalijaga. Sunan Muria, menurut tradisi, mewarisi kepiawaian mendalang, mencipta tembang sinom dan kinanthi, serta memadukan ajaran tauhid dengan nasihat etika sosial dalam balutan seni budaya.
Posisi ini menempatkan Sunan Muria sebagai generasi penerus di lingkungan elite spiritual yang memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat Jawa peralihan abad ke-15 hingga ke-16. Sebagaimana diuraikan dalam berbagai babad, Sunan Kalijaga sendiri masyhur sebagai murid Sunan Bonang dan pewaris tradisi sufistik yang kreatif mengemas dakwah melalui media kebudayaan seperti wayang, gamelan, suluk, hingga laku tapa brata yang sinkretik.
Masa hidup Sunan Muria diperkirakan beririsan dengan konsolidasi kekuasaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Dalam konteks politik ini, jaringan Wali Songo bukan hanya barisan ulama spiritual, tetapi juga pilar ideologis yang menopang legitimasi raja-raja Demak yang masih berkerabat dengan trah Majapahit.
Dinamika sosial-politik ini menjelaskan bagaimana jalur pendidikan keilmuan Sunan Muria tidak hanya terikat pada satu figur, melainkan berkelindan dalam jejaring para wali, para bangsawan lokal, hingga guru-guru sufi yang mengembara dari pesisir ke pedalaman.
Tapa Ngeli: Askese di Pinggir Sungai
Salah satu fragmen penting dalam legenda Sunan Muria yang beredar luas ialah praktik Tapa Ngeli—sebuah bentuk asketisme yang meniru laku para pertapa Hindu-Buddha Jawa, tetapi kemudian diislamisasi dalam makna spiritual sufistik.
Dikisahkan bahwa Sunan Muria bersemadi dengan menghanyutkan diri di sungai, membiarkan tubuhnya larut mengikuti arus air selama waktu yang tak ditentukan, hingga semak-belukar tumbuh menutupi jasadnya. Tapa Ngeli menjadi simbol penyucian diri, penyerahan total pada kehendak Ilahi, serta pengendapan nafsu keduniawian yang dalam kosmologi Jawa diumpamakan sebagai bagian dari proses menaklukkan “badan kasar”.
Kemiripan ritual ini dengan praktik spiritual ayahandanya, Sunan Kalijaga, tidak bisa diabaikan. Sunan Kalijaga dalam berbagai suluk dikisahkan melakukan tapa brata di pinggir sungai selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang yang memberinya tuntunan ruhani.
Laku tapa di pinggir air ini sesungguhnya bukan semata folklore, melainkan penanda transformasi simbolik: air yang mengalir mempresentasikan tasawuf sebagai jalan spiritual yang fleksibel, meresap ke segala penjuru kehidupan masyarakat Jawa, menembus sekat-sekat tradisi pra-Islam dengan menautkan makna-makna baru.
Dewa Ruci dan Falsafah Bahrul Wujûd
Menarik untuk mencermati bahwa narasi Tapa Ngeli Sunan Muria senafas dengan cerita wayang Dewa Ruci, lakon yang dipopulerkan Sunan Kalijaga di lingkaran masyarakat pesisir Jawa. Dewa Ruci atau Nawa Ruci sesungguhnya merupakan adaptasi dari naskah kuno karya Empu Syiwamurti pada masa akhir Majapahit, lalu diislamisasi melalui suluk dan pertunjukan wayang.
Inti kisahnya menuturkan perjalanan Bhima (Wrekodhara), tokoh Pandawa yang kuat dan berwatak keras, yang masuk ke samudera Lawana-udadhi tanpa batas, menembus lapisan kesadaran material menuju kedalaman diri, di mana ia berjumpa Sang Hyang Murti Nawa Ruci yang menyingkap hakikat Kebenaran Sejati.
Dalam suluk yang ditafsirkan Sunan Kalijaga, Bhima sebagai Wrekodhara (serigala) disamakan dengan nafs hayawaniyyah, yaitu dorongan nafsu kebinatangan yang harus ditaklukkan oleh seorang salik. Samudera luas, Lawana-udadhi, diterjemahkan ke dalam istilah bahrul wujûd, lautan wujud yang melambangkan kesatuan makrokosmos dan mikrokosmos dalam pandangan wujudiyah. Wejangan Nawa Ruci kepada Bhima menjadi simbol penyingkapan tabir keesaan Tuhan, menempatkan manusia di antara pengetahuan zâhir dan bathin.
Kemungkinan besar, Sunan Muria mewarisi tafsir sufistik ini dari Sunan Kalijaga. Jejak spiritual semacam ini menegaskan bahwa keilmuan Sunan Muria bukan hanya sekadar fiqh atau syariat formal, tetapi menembus ke ranah mistik Islam Jawa, di mana dakwah bukan sekadar pengajaran hukum Islam, melainkan juga penataan batin masyarakat agar dapat menerima tauhid melalui simbol-simbol budaya lokal.
Jejak Guru dan Murid: Sunan Ngerang dan Kisah Maling Kapa
Rantai keilmuan Sunan Muria semakin menarik ketika dihubungkan dengan figur Sunan Ngerang, atau Ki Ageng Ngerang, seorang guru spiritual yang dalam banyak cerita lisan disebut pernah mendidik Sunan Muria, Sunan Kudus, hingga Adipati Pathak Warak. Kisah ini populer dikenal sebagai legenda Maling Kapa, yang menyiratkan ketegangan etis sekaligus dramatis dalam proses belajar para murid Wali Songo.
Diceritakan, pada suatu ketika Sunan Ngerang mengadakan syukuran merayakan usia putrinya, Dewi Roroyono, yang genap dua puluh tahun. Para murid — Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Pathak Warak, Kapa dan Gentiri — hadir untuk menghormati guru mereka. Di sinilah terjadi insiden yang memercik konflik: Pathak Warak, terpukau kecantikan Dewi Roroyono, bertindak lancang membawa lari sang putri ke Mandalika, Jepara. Peristiwa ini bukan sekadar drama percintaan, melainkan juga simbol ujian moralitas bagi murid-murid yang sedang menempuh laku ruhani.
Raden Umar Said, dalam fragmen ini, tampil sebagai figur penegak kehormatan. Ia berhasil membebaskan Dewi Roroyono dari cengkeraman Pathak Warak, sekaligus mengalahkan dua saudara, Kapa dan Gentiri, yang dikisahkan berkhianat.
Dalam naskah-naskah lisan, dikisahkan pula Sunan Ngerang berikrar menikahkan putrinya dengan siapa pun yang mampu membawanya pulang dengan selamat. Maka, perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono pun menjadi nyata. Dari sinilah Sunan Muria tidak hanya tampil sebagai murid Sunan Ngerang, tetapi juga menantunya.
Baca Juga : Mas Ibin Resmikan Masjid Nur Hidayah, Simbol Gotong Royong Warga Gedog
Perkawinan Politik: Jaringan Kekuasaan dan Dakwah
Dimensi perkawinan Sunan Muria sesungguhnya tidak berhenti pada hubungan personal dengan Sunan Ngerang. Dalam babad-babad pesisir disebutkan bahwa Raden Umar Said juga menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung — yang tak lain ayah Sunan Kudus. Dengan demikian, Sunan Muria terhubung melalui ikatan pernikahan ke dua jalur wali yang berpengaruh di wilayah pesisir utara Jawa. Pernikahan ini bukan semata-mata urusan keluarga, melainkan juga memperkuat jaringan legitimasi sosial-politik di tengah pusaran perebutan pengaruh antara kerajaan Islam Demak dengan sisa-sisa aristokrasi Majapahit.
Melalui perkawinan ini, Sunan Muria memegang posisi strategis dalam menata dakwah di kawasan Muria, Kudus, dan Jepara. Bukit Muria yang kala itu masih berhutan lebat menjadi pusat spiritualitas baru, di mana ajaran Sunan Muria meresap ke masyarakat petani, nelayan, dan perajin. Dalam studi-studi mutakhir, pendekatan dakwah di wilayah Muria kerap ditandai dengan model penyelarasan kosmologi lokal — memadukan keyakinan animistik setempat dengan nilai-nilai Islam, membangun pesantren-pesantren awal, serta mempopulerkan pertunjukan wayang sebagai media ajar sufistik.
Jaringan Wali Songo: Ideologi, Spiritualitas, dan Strategi
Maka tidak mengherankan bila jejak Sunan Muria selalu dipahami dalam kerangka jaringan Wali Songo. Di balik kisah Tapa Ngeli atau lakon Dewa Ruci, terbentang realitas historis bahwa para wali bukan hanya pembawa agama, tetapi juga aktor ideologis yang memainkan peran kunci dalam menjembatani transformasi sosial di Jawa pasca runtuhnya Majapahit. Keilmuan para wali — termasuk Sunan Muria — tidak berdiri di menara gading keilmuan semata, melainkan membumi melalui laku asketisme, jaringan perkawinan politik, dan integrasi dakwah dengan tatanan budaya agraris.
Spiritualitas Sunan Muria pun tidak terlepas dari konteks perlawanan simbolik terhadap dominasi struktur lama. Laku tapa di pinggir sungai, penghanyutan diri ke arus air, hingga tafsir Dewa Ruci, pada dasarnya adalah ekspresi penaklukan ego kolektif Jawa-Hindu yang perlahan-lahan diislamisasi. Dalam makna sosiologis, gerakan dakwah di lereng Muria juga menjadi strategi mengimbangi pusat kekuasaan Demak yang lebih feodal, dengan menumbuhkan basis keagamaan yang dekat dengan rakyat kebanyakan.
Tapa Ngeli sebagai Metafora Zaman
Kisah Jejak Keilmuan Sunan Muria memang tidak selalu didukung bukti tertulis yang definitif. Namun, narasi lisan, babad, dan pertunjukan rakyat telah memelihara ingatan kolektif tentang bagaimana laku spiritual seperti Tapa Ngeli dan tafsir Dewa Ruci menjelma menjadi simbol pengembaraan batin masyarakat Jawa. Dalam lorong waktu, kita melihat bahwa Sunan Muria bukan semata seorang ulama yang bersemedi di pinggir sungai, melainkan juga penganyam jaringan keilmuan, pewaris falsafah wujudiyah, dan penjaga tradisi dakwah Wali Songo yang lentur membaca ruang dan zaman.
Dalam pembacaan historiografi kritis, kita pun diingatkan bahwa di balik legenda selalu terdapat lapis-lapis realitas sosial: pergulatan ideologi Islam dengan sisa-sisa Majapahit, perkawinan politik sebagai strategi legitimasi, serta penaklukan ‘dendam sejarah’ melalui integrasi nilai-nilai sufistik ke dalam budaya agraris Jawa. Tapa Ngeli, dengan demikian, bukan sekadar penghanyutan diri di sungai Muria, melainkan penanda bahwa aliran ilmu pengetahuan pun senantiasa mengalir, menembus sekat-sekat zaman, menghidupkan rantai tradisi yang terus mengalir di lereng Muria hingga hari ini.
Menaklukkan Begal, Menyentuh Hati Lewat Wayang: Kisah Dakwah Sunan Muria
Dari lereng Gunung Muria, Islam mengalir bukan dalam bentuk dekrit kekuasaan, melainkan sebagai alunan tembang dan bayang wayang. Di wilayah-wilayah utara pesisir Jawa—Jepara, Tayu, Juwana, hingga Kudus—nama Sunan Muria dikenang bukan hanya sebagai ulama, tetapi sebagai seniman spiritual, penyatu iman dan budaya. Dalam narasi sejarah Islam Nusantara, Sunan Muria berdiri sebagai penghubung antara warisan Hindu-Buddha Majapahit dan kosmologi Islam yang disampaikan dalam bahasa rakyat.
Sebagai putra Sunan Kalijaga dan menantu Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak, Sunan Muria berada pada simpul penting jaringan kekuasaan religio-politik abad ke-16. Namun, kekuasaannya tak terletak pada angkatan bersenjata, melainkan pada kemampuannya membentuk struktur makna baru dalam kebudayaan lokal. Di tengah pergeseran besar pasca-runtuhnya Majapahit, ketika pengetahuan tentang kakawin dan bahasa Sansekerta merosot drastis, Sunan Muria hadir dengan pendekatan yang membumi. Bersama para wali lainnya, ia menciptakan bentuk sastra baru yang lebih sederhana dan komunikatif: tembang macapat.
Menurut klasifikasi tradisi sastra Jawa, Sunan Muria dikaitkan dengan dua bentuk tembang cilik (sekar alit): Sinom dan Kinanthi. Kedua jenis tembang ini tak hanya mudah dihafal, tetapi juga penuh nuansa didaktik. Di tangan Sunan Muria, syair menjadi sarana pendidikan spiritual. Nilai-nilai Islam diselipkan dalam cerita-cerita etis yang menggugah batin, disampaikan dalam bentuk yang telah dikenali masyarakat sejak masa Hindu-Buddha.
Dakwahnya tidak berhenti pada sastra. Sunan Muria dikenal sebagai dalang yang kerap mementaskan lakon carangan, seperti Dewa Ruci, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, dan Semar Ambarang Jantur. Pertunjukan wayang ini bukan sekadar hiburan, melainkan sarana penyampaian tauhid dan akhlak Islam, yang dikemas dalam narasi simbolik dan alegoris.
Melalui karakter Bima yang mencari makna sejati dalam tubuhnya sendiri (Dewa Ruci), ia menanamkan pesan sufistik dalam jiwa rakyat. Sunan Muria melanjutkan tradisi ayahandanya, yang merombak seni pewayangan menjadi kendaraan dakwah.
Dalam praktik keagamaan, Sunan Muria tidak memutus rantai tradisi lokal, tetapi membentuknya ulang. Tradisi bancakan—yang semula berupa sesaji kepada roh—diubah menjadi kenduri, yakni doa bersama kepada leluhur dengan mengedepankan bacaan Islam. Ia memperkenalkan konsep spiritualitas yang selaras dengan nilai-nilai lokal, bukan menegasinya.
Namun, dakwah Sunan Muria bukan tanpa dimensi politik. Ketika Sultan Trenggana wafat pada 1546, Demak dilanda konflik suksesi. Sunan Muria berpihak pada ahli waris Trenggana, berseberangan dengan Sunan Kudus yang mendukung Arya Penangsang. Kesetiaan ini memperkuat posisinya di mata kesultanan. Keberadaan tujuh belas makam prajurit Demak di sekitar makam Sunan Muria menunjukkan bahwa wilayah dakwahnya juga dilindungi secara militer, mencerminkan simbiosis antara kekuatan spiritual dan politik.
Sunan Muria juga dikenal sebagai pemuka yang menjaga ketertiban sosial. Legenda menyebut bahwa ia berhasil menaklukkan para begal yang meresahkan masyarakat. Salah satu kisah menyebut Kyai Mashudi, mantan perampok kejam yang bertobat setelah bertemu Sunan Muria. Kyai Mashudi kemudian dikenal sebagai sosok saleh, menjadi lambang keberhasilan pendekatan dakwah persuasif berbasis spiritualitas.
Dalam konteks sejarah Islam Jawa, kisah ini menandai momen penting ketika dakwah bukan hanya persoalan penyebaran dogma, tetapi perjuangan panjang membentuk struktur makna baru dalam masyarakat yang tengah bertransformasi. Sunan Muria bukan sekadar pendakwah, melainkan pemahat budaya yang berhasil membingkai Islam dalam nyanyian, lakon, dan tradisi.
Kini, makamnya di Gunung Muria menjadi titik ziarah, bukan karena kekuasaannya, melainkan karena pengaruh spiritual yang melintasi zaman. Seperti tembang yang terus dinyanyikan, warisannya tak pernah diam. Ia adalah suara lembut yang menaklukkan kekerasan dengan seni, menyentuh hati rakyat lewat bahasa yang mereka pahami: kebudayaan.